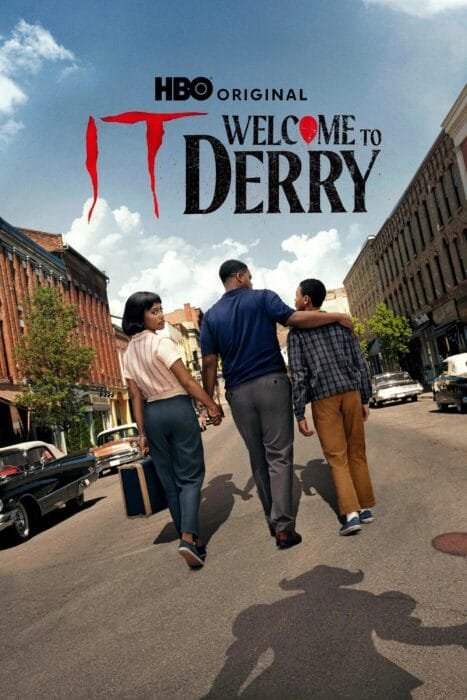Desir.id – Medan | Sudah lama film adaptasi komik terjebak dalam dua pendekatan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, banyak yang memilih jalur gelap dan “realistis”, mendekonstruksi karakter hingga nyaris menghapus akar idealismenya. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang justru memosisikan kisah para pahlawan super ini sebagai hiburan ringan yang tidak perlu dianggap serius, seolah-olah karena sumber materinya penuh hal mustahil, maka filmnya pun harus selalu penuh lelucon dan tidak perlu punya bobot emosional. Padahal, adaptasi komik tidak harus memilih salah satu ekstrem itu. Film bisa tetap menyuguhkan warna, imajinasi, dan absurditas khas komik, tapi tetap membawa cerita yang punya makna dan ketulusan.
Dua film terbaru, Superman dan The Fantastic Four: First Steps, menunjukkan bahwa menjadi “comicbooky” bukanlah kelemahan. Justru, dengan merangkul sepenuhnya identitas mereka sebagai karakter komik, kedua film ini berhasil menawarkan sesuatu yang segar, jujur, dan terasa relevan bagi penonton masa kini.
Tidak hanya itu, keduanya juga hadir di momen yang sangat krusial bagi franchise mereka masing-masing. DC Universe yang baru saja dibentuk kembali masih dalam tahap membangun pondasi awal, dan Superman menjadi langkah layar lebar pertama yang akan menentukan kelangsungan semesta barunya. Film ini bukan hanya tentang memperkenalkan kembali karakter ikonik, tapi juga membawa beban besar sebagai ujian kepercayaan pertama bagi penonton terhadap visi baru James Gunn dan tim kreatif DCU. Jika gagal, seluruh struktur naratif yang sedang dirancang bisa runtuh bahkan sebelum sempat berdiri kokoh.
Di sisi lain, The Fantastic Four: First Steps datang di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap Marvel Cinematic Universe. Setelah fase panjang yang penuh ketidakpastian dan respons dingin terhadap beberapa rilisan terakhir, arah MCU menuju dua film Avengers selanjutnya terasa rapuh. Film ini pun seolah jadi taruhan besar Marvel untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa menawarkan sesuatu yang segar dan bermakna. Dengan memilih untuk berdiri di luar semesta utama, film ini justru berhasil menyuntikkan harapan baru. Ia tidak hanya memperkenalkan kembali salah satu tim superhero paling penting Marvel, tapi juga mengingatkan penonton akan kualitas narasi dan dunia yang dulu membuat MCU dicintai.
Superman karya terbaru dari DCU bukan sekadar reboot, tapi sebuah perkenalan ulang yang terasa penting bagi generasi sekarang. David Corenswet memerankan Superman dengan karisma khas boy scout yang sudah lama tidak kita lihat. Yang lebih menarik, perbedaan antara Clark Kent dan Superman di sini terasa jelas, dari cara bicara hingga gesture tubuh. Karakter ini diperlihatkan tidak selalu percaya diri, sering kalah debat, bahkan kadang terlihat canggung saat bertarung. Namun, semua itu bukan untuk merendahkan sang tokoh, melainkan bagian dari pembangunan karakter yang membuatnya terasa lebih manusiawi tanpa menghilangkan idealismenya.
Salah satu aspek komik yang berhasil ditranslasikan dengan baik ke film adalah kehadiran Krypto, anjing super yang menjadi teman setia Superman. Meski terdengar absurd, kehadiran Krypto justru memberi warna tersendiri, menambah kesan segar sekaligus menguatkan nuansa comicbooky yang diusung film ini. Hal ini menunjukkan bahwa film tidak takut menghadirkan elemen-elemen khas komik yang mungkin terdengar lucu atau tidak biasa, tapi justru memperkaya cerita dan karakter.
Lois Lane versi Rachel Brosnahan juga meninggalkan kesan kuat. Ia bukan hanya love interest, tapi punya peran penting sebagai pribadi yang mandiri, berani, dan tetap charming. Sementara itu, Lex Luthor versi Nicholas Hoult tampil sebagai ancaman nyata. Ia bukan mastermind yang tenang, tapi seorang jenius yang dirasuki iri dan kebencian. Karakter-karakter pendukung seperti Metamorpho, Justice Gang, tim Daily Planet, hingga kaki tangan Lex juga mendapat porsi yang pas. Meskipun film ini sempat terasa padat, semua elemen akhirnya menyatu dengan mulus. Adegan aksi dan visual memberi pengalaman imersif, terutama saat Superman terbang. Beberapa bagian terasa agak kurang pas dalam pacing dan humor, tapi tidak sampai merusak keseluruhan. Film ini menjadi langkah awal yang solid untuk arah baru DCU.
Salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan ini adalah pendekatan James Gunn sebagai arsitek utama DCU. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu mengedepankan comic accuracy dalam setiap proyek adaptasi komiknya, baik itu saat menangani Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, maupun serial Peacemaker. Pendekatan ini tak hanya soal visual atau nama-nama karakter yang diambil langsung dari komik, tapi juga tentang memahami esensi moral dan dinamika karakter yang sudah melekat sejak awal penciptaannya. Untuk Superman, ini menjadi fondasi penting dalam mengembalikan karakter ke akarnya: sebagai simbol harapan, bukan hanya kekuatan. Visi ini menjadi benang merah yang menjanjikan arah baru DCU yang lebih jujur terhadap materi sumbernya.
Lebih dari itu, film ini juga menunjukkan keberaniannya dalam menyuarakan sikap. Salah satu konflik utama dalam cerita melibatkan Jarhanpur, sebuah negara kecil yang ditindas dan diduduki secara agresif oleh Boravia, negara besar yang mengklaim wilayah dan sumber dayanya. Cara film menggambarkan ketimpangan kekuasaan, ketidakberdayaan warga sipil, hingga dilema moral karakter-karakter yang terlibat, dengan cepat dibaca oleh banyak penonton sebagai sindiran yang cukup jelas terhadap situasi Palestina dan Israel. Meski tidak menyebut nama secara langsung, posisi Superman dalam konflik tersebut terasa tegas: berpihak pada rakyat yang terjajah. Tak heran jika beberapa pihak mulai menyuarakan boikot terhadap film ini, menyebutnya sebagai film “anti-Israel”. Namun, pendekatan ini justru memperkuat nuansa relevan dari karakter Superman, yang sejak awal memang diciptakan untuk berdiri di pihak yang tertindas. Film ini menyampaikan pesan tersebut dengan cukup playful, tapi tidak kehilangan ketajaman dalam menunjukkan sisi mana yang layak mendapatkan simpati ketika agresi terhadap satu negara terjadi.
Sementara itu, Marvel menawarkan sesuatu yang berbeda lewat The Fantastic Four: First Steps. Film ini berdiri di luar kontinuitas utama MCU, dan justru berhasil karena pilihan itu. Film ini memberikan penghormatan besar terhadap asal usul karakter dan ceritanya yang bermula pada era 60-an dari pikiran dan tangan Jack Kirby dengan bantuan Stan Lee. Tidak hanya lewat kostum dan gaya bercerita, tetapi juga lewat ruang lingkupnya yang menyentuh sisi kosmik khas komik. Walau tidak bisa sepenuhnya mencapai tingkat warna atau imajinasi liar seperti yang biasa terlihat di panel-panel Kirby, film ini tetap menampilkan sekuens luar angkasa dan elemen dimensi lain yang terasa sebagai upaya yang jujur dan niat untuk menangkap semangat eksploratif dan fantastis dari karya aslinya. Imajinasi kosmik ini hadir sebagai bagian dari penghormatan terhadap semesta luas yang dulu menjadikan Fantastic Four pelopor cerita-cerita Marvel bertema penemuan, petualangan, dan sains-fiksi tingkat tinggi.
Setting retrofuturistik juga merupakan fondasi atmosfer yang terasa autentik. Dunia dalam film ini dibangun dengan sangat teliti, seolah benar-benar berasal dari sejarah alternatif. Lebih dari sekadar nostalgia, pendekatan ini juga memberi ruang bagi karakter-karakter Fantastic Four untuk bersinar secara organik.
Kualitas itu tidak lepas dari tangan Matt Shakman sebagai sutradara. Sebelumnya ia mengarahkan WandaVision, sebuah proyek yang juga dipuji karena kemampuannya dalam memberi penghormatan kepada berbagai era televisi dan pop culture, sekaligus menunjukkan kepekaan terhadap dinamika dan perkembangan karakter. Sensibilitas yang sama terbawa ke Fantastic Four, dan terlihat jelas dalam caranya membentuk hubungan antar anggota tim. Shakman adalah pilihan yang tepat untuk menangani proyek ini, dan hasil akhirnya membuktikan hal itu. Dinamika keluarga dalam film terasa sangat hangat, natural, dan tidak pernah terasa dipaksakan. Penonton bisa langsung percaya bahwa mereka adalah satu keluarga.
Joseph Quinn tampil sebagai Johnny Storm yang tetap impulsif, tapi sekarang punya sisi lebih dewasa. Vanessa Kirby sebagai Sue Storm tampil sebagai jiwa tim yang tenang dan stabil, sekaligus seorang ibu yang tangguh. Ben Grimm versi Ebon Moss-Bachrach mencuri perhatian dengan vibe “om keren” yang nge-blend sempurna dengan Johnny. Reed Richards yang diperankan Pedro Pascal terlihat jenius sekaligus terbebani oleh harapan dunia, namun tetap menyisakan kelembutan sebagai suami dan ayah baru. Ini adalah versi tim Fantastic Four yang paling terasa hidup sejauh ini.
Kejutan terbesar datang dari Galactus yang akhirnya diberi perlakuan layak. Dengan suara berat Ralph Ineson dan efek visual yang tidak terasa terlalu artifisial, kehadirannya benar-benar menakutkan. Silver Surfer versi Julia Garner juga tampil meyakinkan lewat kombinasi performa dan desain yang konsisten. Meskipun alur ceritanya cukup bisa ditebak, terutama bagi yang sudah mengikuti semua materi promosi, film ini tetap punya banyak nilai lebih. Beberapa efek CGI memang kurang rapi, terutama saat menampilkan Franklin kecil, tapi secara keseluruhan tidak merusak pengalaman menontonnya.
Yang membuat kedua film ini menarik bukan hanya karena mereka sukses sebagai adaptasi, tapi karena mereka berani tampil setia pada akar komiknya. Tanpa malu-malu, keduanya membawa kembali warna, idealisme, dan semangat heroisme yang dulu menjadi ciri khas superhero. Tapi mereka tidak hanya meniru masa lalu. Mereka menerjemahkannya ke dalam konteks yang lebih relevan dan manusiawi. Hasilnya adalah pengalaman sinematik yang tidak hanya menghormati karakter, tapi juga mengajak penonton untuk merayakan keunikan dunia komik. Sebuah arah baru yang terasa lebih jujur, dan akhirnya terasa benar.
Rate Superman: ⭐⭐⭐⭐½
Rate The Fantastic Four: First Steps: ⭐⭐⭐⭐
Penulis: Arya Yudhistira Wicaksono